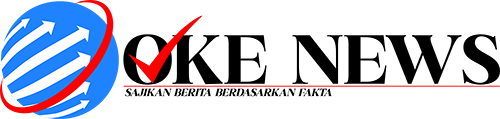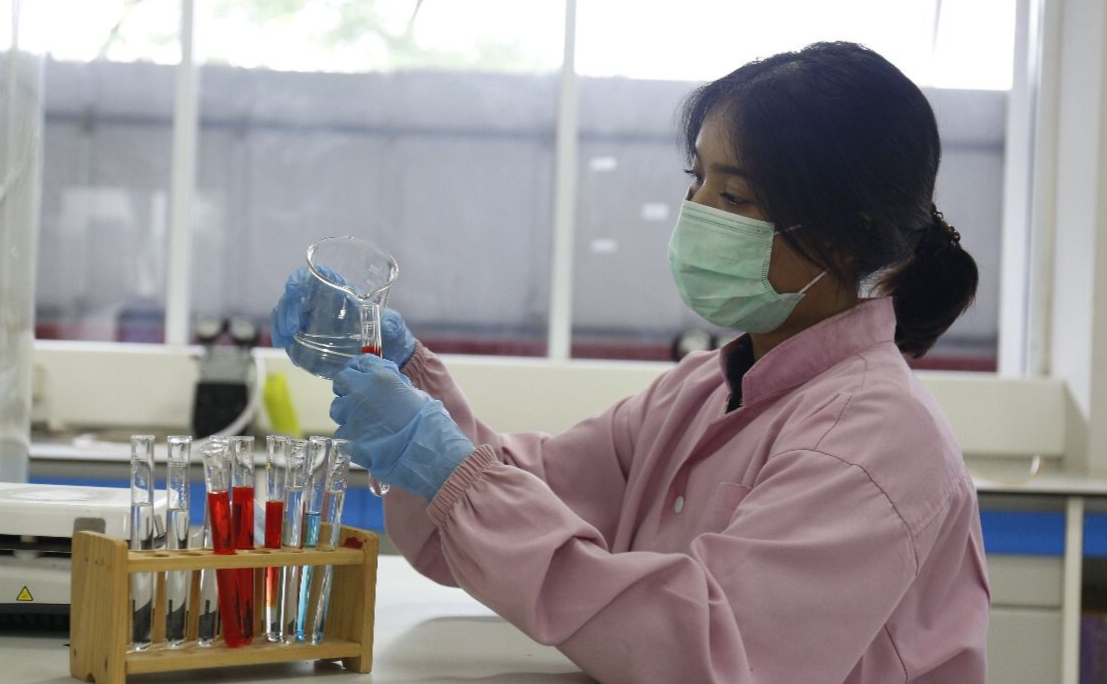Di tanah Minangkabau, rendang bukan sekadar makanan, ia adalah peradaban yang dimasak perlahan. Namun di ujung pesisir selatan Sumatera Barat, tepatnya di Kanagarian Surantih, Kecamatan Sutera, ada satu varian rendang yang membuat siapa pun berhenti sejenak dan merenung, Rendang Paku. Tak ada daging sapi, tak ada kerbau, tak ada lauk mewah di sana. Yang menjadi bintang utama justru tumbuhan liar yang tumbuh di lembah lembap dan tepi sungai yaitu paku.
Dalam pandangan masyarakat setempat, paku bukan sekadar sayuran. Ia adalah anugerah alam yang tak pernah meminta untuk ditanam, tapi selalu hadir ketika manusia membutuhkan. “Kalau musim hujan, paku tumbuh di mana-mana. Tinggal petik, rebus, dan jadilah rendang,” kata Uni Rosma, seorang ibu rumah tangga di Surantih, sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu menyimpan falsafah besar, bahwa kehidupan sejati ada dalam keseimbangan antara alam dan manusia.
Dari Alam ke Dapur
Membuat rendang paku bukan perkara mudah. Ia menuntut kesabaran yang panjang, ketelatenan yang diwariskan, dan cinta yang tak tergesa. Proses dimulai dari memilih paku muda, batangnya tidak boleh terlalu keras agar tidak getir ketika dimasak. Setelah dibersihkan, bahan ini disatukan dengan bumbu halus yang terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Santan kental dari kelapa tua diperas dengan tangan, lalu dimasukkan ke dalam kuali besar di atas tungku kayu bakar.
“Kalau api terlalu besar, santan pecah. Kalau terlalu kecil, tak jadi rendang. Semua harus seimbang,” ujar Mak Uni, tetua dapur di nagari itu. Dari situ tampak bahwa memasak bagi orang Minang bukan semata urusan perut, melainkan latihan spiritual. Setiap gerakan mengaduk, setiap percikan minyak, adalah meditasi, seni menjaga kesabaran dan rasa hormat pada bahan yang diberikan alam.
Selama tiga jam penuh, rendang paku diaduk perlahan. Aroma santan yang berubah jadi minyak berpadu dengan wangi rempah dan kayu bakar. Warna paku yang hijau perlahan menjadi kecokelatan gelap, hingga akhirnya hampir kehitaman, warna yang disebut orang Surantih sebagai “warna adat”, tanda masakan sudah mencapai kesempurnaan.
Dan ketika rendang paku matang, rasanya tak bisa disamakan dengan apa pun. Ia gurih, sedikit pahit, manis samar, dan ada aroma tanah lembap yang hanya bisa dihasilkan dari tumbuhan liar. Rasa pahit itu bukan cacat, melainkan keseimbangan, pengingat bahwa hidup tak selalu manis, tapi selalu bisa dinikmati.
Filosofi dalam Setiap Suapan
Rendang paku, seperti halnya rendang daging, adalah simbol identitas dan filosofi hidup orang Minangkabau. Ia lahir dari prinsip alam takambang jadi guru, alam terbentang menjadi guru.
Ketika daging sulit diperoleh, masyarakat pesisir tak mengeluh. Mereka memandang sekitar, melihat pakis yang tumbuh bebas di tanah lembap, lalu menjadikannya makanan berkelas. Di situ tampak kecerdikan, kreativitas, dan adaptasi, ciri khas peradaban Minangkabau yang selalu mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri.
Dalam upacara adat, rendang paku sering hadir sebagai hidangan penyerta rendang lokan atau gulai lado. Di acara batagak penghulu, makan bajamba, atau peringatan keagamaan, ia disajikan di daun pisang panjang bersama nasi putih, sambal lado hijau, dan ikan kering.
Kaum ibu memasak bersama, sementara kaum bapak menyiapkan kayu bakar dan tempat makan. Semua bekerja dalam semangat gotong royong yang masih hidup kuat di pesisir Minangkabau.
“Kalau rendang paku sudah naik di meja, artinya semua orang sudah berkumpul. Itu tanda nagari masih hidup,” ujar salah satu ninik mamak di Surantih. Kata-kata itu menegaskan bahwa rendang paku lebih dari sekadar kuliner, ia adalah simbol persaudaraan, lambang keutuhan sosial, dan bukti bahwa tradisi bisa menjadi perekat di tengah perubahan zaman.
Rendang, Alam, dan Identitas
Dalam konteks budaya Minang, setiap jenis rendang punya cerita sendiri. Rendang daging menandakan kemewahan dan kehormatan. Rendang lokan mewakili pesisir yang kaya hasil laut. Sedangkan rendang paku adalah wujud kesederhanaan yang luhur, bukti bahwa cita rasa sejati tak butuh kemewahan, cukup dengan kesabaran dan penghormatan pada alam.
Yang menarik, masyarakat Surantih percaya bahwa siapa pun yang sabar memasak rendang paku, akan menjadi orang yang sabar dalam hidup. “Tangan yang kuat mengaduk rendang, biasanya hati yang kuat pula menahan amarah,” begitu ujar pepatah lama. Rendang, dalam pandangan mereka, bukan sekadar resep, ia adalah guru kehidupan.
Kini, di tengah gempuran makanan cepat saji, rendang paku menjadi semacam bentuk perlawanan kultural. Ia mengingatkan kita bahwa kelezatan tak bisa dipercepat, dan cita rasa sejati butuh waktu, kesabaran, dan sentuhan manusia. Masakan ini juga menunjukkan betapa ekologi dan budaya berjalan beriringan, masyarakat hanya mengambil apa yang dibutuhkan dari alam, dan alam pun terus memberi dengan murah hati.
Dari Dapur ke Dunia
Meski tidak sepopuler rendang daging, rendang paku mulai menarik perhatian wisatawan dan peneliti kuliner. Beberapa kelompok perempuan di Surantih kini menjual rendang paku kering sebagai oleh-oleh khas daerah pesisir. Dengan kemasan modern namun tetap mempertahankan cita rasa asli, mereka membuktikan bahwa warisan lokal bisa hidup berdampingan dengan industri kreatif.
“Kalau rendang daging dikirim ke luar negeri, rendang paku kami kirim ke hati orang kampung,” canda seorang ibu penjual di pasar nagari. Candaan itu menyentuh, karena benar adanya, rendang paku bukanlah soal komersial, tapi soal kebanggaan dan identitas.
Di tengah dunia yang berubah cepat, rendang paku berdiri teguh sebagai pengingat bahwa akar budaya harus tetap dijaga. Bahwa dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi ruang suci di mana nilai-nilai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Rendang paku bukan sekadar kuliner khas pesisir, ia adalah kisah tentang manusia dan alam yang saling memahami. Ia mengajarkan bahwa dari sesuatu yang sederhana, bisa lahir keindahan dan kebijaksanaan yang abadi. Seperti pepatah Minang yang mengatakan, “Alam takambang jadi guru, dapur jadi surau yang mendidik rasa.”
Dan setiap kali aroma santan yang menguap dari tungku menyebar ke udara pesisir Surantih, itu bukan hanya tanda masakan sedang dimasak, tapi juga tanda bahwa budaya masih bernapas.
Oleh: Muhammad Fawzan